
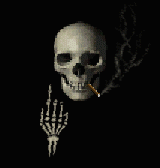
Pendahuluan
GBHN 1993 antara lain memberikan petunjuk bahwa pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tata ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif.
Selanjutnya GBHN 1993 juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, di samping untuk memberi kemanfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sumber daya alam yang terbaharukan harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar kemampuannya untuk memperbaharui diri selalu terpelihara. Sumber daya alam yang tidak terbaharukan harus digunakan sehemat mungkin dan diusahakan habisnya selama mungkin. Kegiatan di sektor yang mengelola sumber daya alam dari bumi memiliki potensi untuk merusak lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Oleh karena itu, harus selalu dijaga agar kegiatan pembangunan di sektor-sektor ini memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan salah satu keanekaragaman hayati pada kawasan ekosistem pantai dan pesisir, yaitu terumbu karang, dalam Repelita VI ini juga telah ditetapkan suatu strategi nasional di dalam pengembangan dan pengelolaan, yang disertai dengan upaya konservasi dan rehabilitasi dari terumbu karang tersebut. Oleh sebab itu, kami sangat berbahagia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan Bappenas di dalam upaya untuk menciptakan suatu strategi nasional pengelolaan terumbu karang secara nasional, yang penyusunannya harus tetap mengacu kepada berbagai kebijaksanaan di dalam pembangunan sektor lingkungan hidup dalam Repelita VI dan PJP II dalam jangka panjang.
Peranan Terumbu Karang dalam Pembangunan Nasional
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan mempertimbangkan potensi terumbu karang sebagai salah satu sumber keanekaragaman hayati pada ekosistem pantai dan pesisir di Indonesia, telah banyak upaya yang dilakukan dalam rangka menyusun suatu strategi dalam pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi terumbu karang tersebut. Lebih jauh lagi, dengan mempertimbangkan bahwa potensi terumbu karang yang dimiliki Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, maka pemanfaatan nilai ekonomisnya juga perlu dioptimalkan dan dikendalikan dengan memperhatikan upaya pelestariannya.
Pentingnya suatu strategi dalam pengelolaan terumbu karang secara nasional, terutama dengan mempertimbangkan beberapa peranan penting dari terumbu karang pada skala nasional sebagai berikut:
2. Peranan penting terumbu karang di dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan nilai-nilai ekologis, yang sekaligus diarahkan untuk dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan di tingkat nasional.
3. Peranan terumbu karang sebagai sumber daya alam yang potensial pada skala nasional di dalam menunjang ekspor non migas yang bersumber dari industri pesisir dan maritim.
4. Peranan terumbu karang di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pantai, tanpa mengabaikan upaya pelestarian ekosistemnya secara berkelanjutan.
Dalam rangka mengupayakan sasaran nasional tersebut, diperlukan beberapa langkah-langkah kebijaksanaan yang diarahkan untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan terumbu karang secara nasional sebagai berikut:
2. Pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan dan lestari.
3. Pemanfaatan teknologi yang optimal di dalam penemukenalan, pelestarian, perlindungan dan perbaikan kondisi ekologis terumbu karang.
4. Peningkatan kepedulian dari berbagai intansi terkait di dalam pengelolaan terumbu karang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, serta sekalgus meningkatkan peranserta masyarakat di dalam pengelolaan dan pelestarian terumbu karang.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, peranan terumbu karang sebagai sumberdaya biologis dan ekonomi adalah sangat penting dalam menciptakan kelestarian dari ekosistem pesisir dan pantai serta di dalam peningkatan derajat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pada skala lokal maupun manfaatnya dalam skala nasional. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijaksanaan untuk menyusun suatu strategi nasional pengelolaan terumbu karang yang selalu mengacu kepada beberapa kebijaksanaan pokok di dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam Repelita VI dan PJP II ini.
Komitmen pemerintah yang kuat di dalam upaya pengelolaan sumberdaya terumbu karang secara optimal dan lestari dalam PJP II tersebut, antara lain tercermin dalam penetapan "Biodiversity Action Plan for Indonesia" serta dalam dokumen Repelita VI, khususnya yang terkait dengan program pengelolaan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan maritim. Selain itu, dalam dokumen "Action Plan for Sustainable Development of Indonesia's Marine and Coastal Resources" juga telah dikemukakan beberapa langkah kebijaksanaan dan strategi dalam pengembangan sumberdaya pesisir dan kelautan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, komitmen pemerintah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam suatu Strategi Nasional Pengelolaan Terumbu karang di Indonesia, yang pada saat ini telah sampai kepada tahap penyelesaian secara terkoordinasi antarinstansi terkait.
Pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan merupakan komitmen bersama dari berbagai instansi terkait di tingkat pusat di dalam pengelolaan terumbu karang, yaitu antara lain Kantor Meneg LH, LIPI, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, dan berbagai LSM yang berkiprah di dalam rehabilitasi dan pelestarian terumbu karang.
Komitmen pemerintah tersebut sebenarnya sangat beralasan, mengingat bahwa potensi sumberdaya terumbu karang sangat besar di Indonesia, yang tersebar di 22 propinsi, terutama terkonsentrasi dalam skala besar pada 5 propinsi: Irian Jaya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Riau, serta Sumatera Selatan. Namun demikian, disadari bahwa upaya untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi dan ketersediaan terumbu karang di Indonesia masih perlu terus dilanjutkan dan diakuratkan, dengan adanya perbedaan data inventarisasi antarinstansi terkait, seperti antara data yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan yang menunjukkan cakupan areal seluas 2,17 juta hektare dengan data yang diinventarisir FAO seluas 4,25 juta hektare.
Dalam rangka lebih mengoptimalkan dan melestarikan pengelolaan terumbu karang dalam jangka panjang, diperlukan beberapa upaya pengendalian dan pemanfaatannya secara lebih baik, termasuk di dalamnya upaya konversi terumbu karang menjadi kawasan budidaya yang bernilai ekonomis dan produktif.
Perlunya Koordinasi Antarinstansi dalam Pengelolaan Terumbu Karang
Dengan mempertimbangkan beragamnya keterlibatan berbagai instansi di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah maupun non-pemerintah, di dalam pengelolaan hutan bakau, maka dirasa perlu untuk mengupayakan koordinasi antarinstansi terkait yang diarahkan untuk tersusunnya suatu strategi penanganan yang terpadu dan selaras antarberbagai kepentingan sektoral dan instansional di tingkat nasional maupun daerah.
Dari kenyataan yang ada selama ini, di tingkat pusat saja diketahui setidaknya terdapat 16 departemen/LPND yang terkait dengan program pengelolaan sumberdaya terumbu karang, seperti: Kantor Meneg LH, Departemen Kehutanan, BAPEDAL, LIPI, BAPPENAS, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Kantor Menristek/BPPT, BPS, BAKOSURTANAL, Departemen Parpostel, Departemen Transmigrasi dan PPH, serta Departemen Kesehatan. Dari ke-16 departemen/LPND terkait di atas, dapat ditemukenali 5 instansi utama di dalam pengelolaan secara nasional terumbu karang di Indonesia, yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Kantor Meneg LH, dan BAPEDAL. Belum lagi apabila kita menginventarisasi berbagai lembaga non-pemerintah (LSM) yang juga telah berkiprah dalam pengelolaan hutan bakau, baik yang sifatnya lokal, nasional, maupun internasional.
Dengan demikian, untuk menciptakan kesatuan langkah penanganan, sangat diperlukan suatu pengelolaan yang terpadu dan terkoordinasi antarinstansi terkait tersebut.
Dalam rangka itu, sebenarnya peranan BAPPENAS lebih mengarah kepada upaya untuk mengkoordinasikan dan menterpadukan serta melaraskan berbagai kepentingan sektoral yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang, khususnya dalam kaitannya dengan pengalokasian dana pembangunan yang diperlukan di dalam pengelolaan terumbu karang yang memiliki nilai strategis pada skala nasional. Sedangkan secara substansi/teknis, peran dari Kantor Meneg Lingkungan Hidup sangat diperlukan di dalam melakukan koordinasi terhadap berbagai kepentingan sektoral yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alami terumbu karang secara nasional.
Dalam kaitannya dengan aspek kelembagaan ini, sebenarnya peranan BAPPENAS sebagai suatu lembaga koordinator dalam perencanaan pembangunan nasional, telah tercermin di dalam beberapa dokumen kebijaksanaan yang mengarahkan upaya pengelolaan terpadu dan terkoordinasi lintassektoral sumberdaya hayati secara nasional, seperti pada dokumen "Biodiversity Action Plan for Indonesia" dan "Action Plan for Sustainable Development of Indonesia's Marine and Coastal Resources", dimana dalam penyusunannya BAPPENAS bertindak selaku koordinator. Implikasi dari suatu kegiatan penyusunan langkah kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh BAPPENAS tersebut, diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam implementasinya oleh instansi koordinator yang kompeten secara teknis dan substantif, seperti Kantor Meneg LH dalam koordinasi pengelolaan terumbu karang ini.
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan kebutuhan sumber pendanaan pengelolaan terumbu karang baik secara nasional maupun di tingkat daerah, perlu dikemukakan disini bahwa pada dasarnya sumber pendanaan bagi kegiatan yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang cukup beragam, dari sumber pendanaan dalam negeri yang dialokasikan Pusat (APBN) dan daerah (APBD) hingga yang bersumber dari bantuan luar negeri baik yang dialokasikan kepada Pemerintah (pinjaman dan hibah) maupun kepada lembaga non-pemerintah (LSM). Untuk itu, diperlukan suatu upaya penterpaduan berbagai sumber pendanaan yang potensial di dalam pengelolaan terumbu karang, baik di tingkat nasional maupun lokal, dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilgunanya.
Dalam rangka itu, diperlukan suatu program aksi yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan sektoral dan regional secara lebih optimal dalam pengelolaan terumbu karang. Program aksi tersebut diharapkan dapat mencerminkan suatu upaya yang terpadu dan selaras antarinstansi yang terlibat di dalam mencapai satu sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama, dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia dan potensial untuk dimanfaatkan.
Rencana Aksi Pengelolaan Terumbu Karang secara Terpadu
Dalam rangka perancangan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kepedulian dan peranserta masyarakat setempat dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, khususnya potensi ekosistem terumbu karang di Indonesia, terdapat beberapa kegiatan yang perlu ditindaklanjuti untuk pencapaian beberapa sasaran sebagai berikut:
a. semakin berkembangnya sistem perencanaan dan pengelolaan terumbu karang tepat guna, yang sekaligus dapat menghilangkan pengaruh gangguan terhadap terumbu karang;
b. semakin meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;
c. semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan aparatur daerah untuk lebih mendayagunakan koordinasi dalam perencanaan dan pengelolaan terumbu karang, serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia setempat melalui pendidikan dan pelatihan;
d. semakin tegak dan konsekuennya pelaksanaan peraturan/perundang-undangan dalam perlindungan terumbu karang; serta
e. terbangunnya pusat jaringan informasi dan data rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, untuk melayani informasi yang dibutuhkan dalam rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat luas.
Melalui kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang secara terpadu tersebut, diharapkan dapat diupayakan terlaksananya beberapa kegiatan sebagai berikut:
Bentuk-bentuk pengelolaan dapat berupa penetapan lokasi sebagai kawasan budidaya perikanan, pariwisata atau konservasi. Menerapkan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan seperti perikanan dan pariwisata, sehingga bisa saling mendukung. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat juga dikembangkan semacam warung wisata bahari atau guest house berfasilitas sederhana tapi memadai dan dapat dikelola oleh kelompok masyarakat setempat, sebagai salah satu bentuk wirausaha kecil.
Selain itu, dapat dikembangkan pula penerapan metode pengelolaan terumbu karang sebagai fishing ground (daerah tangakapan ikan) bagi nelayan lokal, mengelola penangkapan sehingga tidak overfishing, dan mengendalikan penangkapan jenis, umur dan ukuran ikan ekonomis. Dengan adanya fishing ground tertentu, nelayan tradisional dapat memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dan terkendali.
Dalam pelaksanaan berbagai upaya di atas, diperlukan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan LSM melalui pengembangan/perumusan tugas pokok dan fungsi LSM dalam meningkatkan kepedulian dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya perlu dilakukan pula baseline data study mengenai keadaan masyarakat pesisir lokasi ekosistem terumbu karang, menyusun konsep pembentukan kelompok swadaya masyarakat, dan pengelolaan dana bergulir (revolving fund), simpan pinjam dan pemasaran hasil, atau kredit usaha dan alternatif lainnya; yang data dan informasi dasarnya diharapkan dapat diberikan oleh pihak LSM.
Melalui beberapa kegiatan pengelolaan dan konservasi terumbu karang di atas, diperlukan beberapa langkah pendahuluan sebagai berikut:
b. Identifikasi masalah dan analisis penyebab kerusakan terumbu karang;
c. Inventarisasi kelompok masyarakat yang terkait dengan perusakan dan pelestarian terumbu karang;
d. Penggalian norma, hukum adat, nilai sosial budaya, dan aturan formal (Perda) dalam pelestarian terumbu karang;
e. Penyusunan tata ruang/peta calon lokasi prioritas yang dilengkapi dengan data biogeofisik, lingkungan sosial dan ekonomi.
Dalam rangka pencapaian sasaran ini diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan metode-metode sosial budaya masyarakat lokal setempat yang bersahabat dengan lingkungan ekosistem terumbu karang, dalam bentuk penyuluhan, kampanye dan persuasi ke berbagai lapisan masyarakat.
Dalam kaitan ini, penggalian akar budaya/hukum adat setempat seperti "SASI" di Maluku menjadi salah satu fokus kegiatan yang perlu diprioritaskan. Untuk itu per;lu dirancang bentuk-bentuk introduksi nilai-nilai dan pengembangan budaya setempat agar masyarakat menjadi lebih perduli melestarikan ekosistem terumbu karang, dan berpartisipasi melindungi ekosistem terumbu karang, serta berpartisipasi melindungi ekosistem terumbu karang dari pengaruh kegiatan ilegal dan overfishing, baik oleh masyarakat lokal maupun pendatang. Pada giliran selanjutnya, sistem budaya yang dikembangkan perlu disebarluaskan ke daerah lain dan didukung secara legalitas melalui peraturan daerah (perda), sehingga nelayan atau masyarakat pendatang dapat menghargai budaya daerah setempat yang berlaku. Dalam rangka peningkatan peranserta dan kepedulian masyarakat setempat di atas, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
b. Penyusunan pola penyuluhan, penerangan dan advokasi kepada masyarakat dalam rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang;
c. Penyebarluasan data dan informasi perencanaan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang pada tingkat lokal;
C. Pengembangan Kelembagaan (melalui Pengembangan Swadaya Masyarakat, Organisasi, Fasilitas)
Dalam upaya itu dilakukan peningkatan pemahaman konsepsi pengelolaan terumbu karang bagi aparat dan pihak yang terkait. Pengembangan kelembagaan ini diupayakan dapat mengakar ke masyarakat, sehingga hubungan antara swasta, pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara harmonis dalam usaha bersama mengelola ekosistem terumbu karang.
Upaya pengembangan kelembagaan, dapat melalui upaya-upaya sebagai berikut:
b. Penyusunan pola dan bentuk pelatihan yang diperlukan bagi aparat pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat setempat;
c. Perlunya dukungan dan komitmen Pemda dalam penyediaan dana daerah dan aparatur pembina teknis masyarakat setempat;
d. Perumusan mekanisme kerja LSM tentang perananannya dalam peningkatan kepedulian dan pendapatan masyarakat.
Kegiatan ini difokuskan pada upaya-upaya untuk menselaraskan antara kebijaksanaan pengelolaan dengan penerapan hukum secara konsisten, sehingga upaya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang dapat lebih terjamin keberhasilannya.
Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga lebih menjamin keberhasilan pengelolaan terumbu karang di daerah. Sistem keamanan laut (Siskamla) yang ada juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat setempat di dalam melindungi dan mengamankan terumbu karang di sekitar mereka.
Dalam rangka penegakan hukum, perlu diupayakan beberapa langkah sebagai berikut:
b. Perumusan tindakan pencegahan bersama-sama masyarakat setempat untuk dijadikan mitra dalam memantau pelaku pemboman dan mengurangi perusakan terumbu karang;
c. Penyusunan batas-batas kewenangan masyarakat, camat, pemuka agama dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumberdaya terumbu karang.
E. Terbangunnya jaringan informasi pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang
Data terumbu karang tersebut selanjutnya dihimpun pada pusat data dapat difungsikan sebagai sumber informasi baik oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat luas untuk berbagai kepentingan. Komponen ini juga meliputi kegiatan penelitian dalam rangka rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang.
Dalam jangka panjang, pada tingkat nasional LIPI akan mengembangkan suatu jaringan informasi pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya laut dan pesisir, yang nantinya akan dapat dijadikan informasi dasar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam budidaya dan konservasi ekosistem terumbu karang. Penyediaan data dan informasi merupakan kebutuhan dasar bagi kegiatan perencanaan dan pengembangan sumber daya hayati terumbu karang. Mengingat bahwa dewasa ini berbagai lembaga pemerintah dan swasta mempunyai data dan informasi pesisir dan pantai yang tersebar di lembaga masing-masing, maka diperlukan suatu upaya untuk mengumpulkan data dan informasi pesisir dan pantai secara terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut sesuai dengan arahan dalam Repelita VI untuk mengembangkan jaringan sistem informasi geografis pesisir dan pantai serta kelautan, dalam rangka mendukung suatu basis data serta jaringannya di berbagai lembaga di tingkat pusat dan daerah.
Persiapan Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Terumbu Karang (COREMAP)
Sehubungan dengan rencana persiapan pelaksanaan proyek COREMAP yang sedianya akan dibiayai melalui pembiayaan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor yang terdiri dari IBRD, ADB, JICA, AusAID dan GEF, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemantapan persiapan proyek COREMAP tersebut, terutama dengan referensi dari pihak Departemen Dalam Negeri (Ditjen Bangda) dan Pemerintah Daerah calon lokasi proyek COREMAP.
- Sesuai dengan rencana semula, rancangan COREMAP akan mencakup 10 propinsi dan 13 kabupaten terpilih di Indonesia, yaitu propinsi-propinsi: (1) Irian Jaya dengan Kab. Biak Numfor, (2) Maluku dengan Kab. Maluku Tengah, (3) Nusa Tenggara Timur dengan Kab. Kupang, (4) Nusa Tenggara Barat dengan Kab. Lombok Barat, (5) Sulawesi Selatan dengan Kab. Pangkep dan Kab. Takalar, (6) Riau dengan Kab. Kepulauan Riau, (7) Sumatera Utara dengan Kab. Nias, (8) Sumatera Barat dengan Kodya Padang dan Kab. Padang Pariaman, (9) Sulawesi Utara dengan Kab. Minahasa dan Kab. Sangihe Talaud, (10) Sulawesi Tenggara dengan Kab. Kendari.
- Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembicaraan dalam fase persiapan, telah disepakati terdapat tigas fase dalam pelaksanaan proyek, dimana pada fase pertama akan difokuskan pada empat propinsi prioritas yaitu Maluku, Sulawesi Selatan, NTT dan Riau.
- Dengan adanya pengurangan jumlah propinsi sasaran pada fase pertama yang dirancang selama tiga tahun sampai dengan tahun 2001, dapat dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- Dalam dua tahun terakhir ini, seluruh 10 propinsi yang direncanakan sejak awal sebagai sasaran COREMAP telah melakukan persiapan yang cukup intensif dan ekstensif, yang antara lain ditunjukkan dengan telah disediakannya dana daerah melalui APBD Tk. I dan Tk. II untuk kegiatan persiapan dimaksud. Secara ringkas kontribusi pendanaan daerah yang telah disediakan oleh masing-masing propinsi calon sasaran COREMAP dapat disarikan sebagai berikut:
| Propinsi/Kabupaten | APBD | Status Persiapan |
|
Rp200 juta
Rp50 juta Rp20 juta Rp53 juta Rp75 juta Rp200 juta Rp75 juta Rp100 juta Rp10 juta Rp100 juta |
Organisasi
proyek terbentuk
LSM aktif dalam penyuluhan Organisasi proyek terbentuk Organisasi proyek terbentuk Organisasi & pokja terbentuk Organisasi, LSM, Unhas Organisasi proyek terbentuk Organisasi & kordinasi baik Organisasi dibentuk & LSM Organisasi proyek terbentuk |
- Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari daerah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antusiasme dan keseriusan dari pemerintah daerah calon lokasi COREMAP telah cukup besar dan telah cukup melakukan persiapan yang cukup intensif dan ekstensif, yang antara lain ditunjukkan dengan telah dibentuknya organisasi persiapan COREMAP tingkat daerah melalui SK Gubernur setempat dan telah dilibatkannya LSM dan perguruan tinggi setempat dalam melakukan disain kegiatan dan penyuluhan kepada masyarakat desa calon lokasi COREMAP.
- Untuk itu, dengan mempertimbangkan berbagai upaya persiapan yang telah dengan serius dilakukan oleh propinsi-propinsi calon lokasi COREMAP, perlu diperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
- Diluar empat propinsi calon lokasi COREMAP, enam propinsi lainnya perlu dilibatkan paling tidak sebagai peninjau (observer) terhadap pelaksanaan proyek di empat propinsi sasaran, guna menjamin keberlanjutan dari kegiatan persiapan dan antusiasme yang mereka telah lakukan selama ini.
- Dalam menjamin keberlanjutan dari fase inisiasi (I) ke dalam fase percepatan dan pelembagaan, sangat perlu disiapkan mulai sekarang ‘institutional setup’ di tingkat daerah, baik di tingkat propinsi maupun dati II, mengingat bahwa tingkat keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan proyek-proyek berbantuan luar negeri di daerah pada umumnya mengalami permasalahan dan isyu dalam implementasi dan keberlanjutannya.
- Kontribusi pendanaan rupiah pendamping terhadap kegiatan COREMAP yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri (PHLN), baik dari pusat dan terutama dari daerah, sangat perlu ditetapkan dalam suatu ‘financing plan’ sejak dini, dalam menjamin komitmen dan kontribusi pendanaan terutama dari dana daerah. Suatu ‘cost table’ dalam setiap fase COREMAP yang dirinci secara tahunan dari tingkat pusat (APBN) hingga kepada tingkat daerah (APBD I dan II) dalam setiap fase COREMAP sangat diperlukan dalam mengantisipasi penyediaan dana pendamping rupiah (RPHLN) setiap tahunnya.
Dalam kaitannya dengan rencana pelaksanaan proyek MREP yang akan berakhir pada akhir tahun depan, serta rencana kelanjutannya dalam MREP-II mulai tahun 1999 mendatang yang akan dibiayai ADB, kedudukan COREMAP juga sangat perlu diintegrasikan dan disinkronkan dengan kegiatan MREP yang telah ada ataupun yang sedang direncanakan, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi pelaksanaan dan pengelolaannya di tingkat daerah. Disarankan bahwa penentuan lokasi COREMAP dapat mengacu kepada rencana zonasi yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh MREP.
Dalam hubungan dengan rencana pembiayaan proyek COREMAP yang beragam sumbernya, baik PHLN maupun dana rupiah, maka mekanisme pengelolaan pembiayaan COREMAP harus dimantapkan sejak dini, belum lagi dengan memperhatikan bahwa pengelolaan proyek akan diserahkan (didesentralisasikan) kepada masyarakat di tingkat lokal. Untuk itu, beberapa hal di bawah ini dapat dijadikan masukan di dalam upaya semakin memantapkan mekanisme pengelolaan dan pembiayaan dari COREMAP.
Sebagai masukan, dapat dikemukakan disini bahwa berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan atas dasar hasil pengamatan, pemantauan dan supervisi terhadap berbagai proyek berbantuan luar begeri PHLN yang sedang dilaksanakan, dapat disarikan beberapa isyu dan permasalahan yang dihadapi baik pada tingkat Pusat maupun di daerah sebagai berikut:
ii. masalah pemahaman dan penyempurnaan dokumen proyek yang masih memerlukan justifikasi (adjustment) lebih lanjut dari para pelaksana kegiatan di lapangan, dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian arahan dokumen proyek awal dengan kondisi riil di lapangan sehingga membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut.
iii. masalah keterbatasan dana pendamping (pusat dan daerah), yang membutuhkan penyesuaian terhadap jadwal penyelesaian dan pelaksanaan proyek, yang sangat potensial menyebabkan terlambatnya/penundaan penyelesaian kegiatan proyek.
iv. masalah rendahnya keterpaduan dengan proyek/program lain, seperti Inpres blockgrant (Dati I, Dati II, Bangdes) dan specific grant (BPW Dati I untuk MREP, kawasan lindung, penghijauan, reboisasi), nampaknya belum sepenuhnya dipertimbangkan keterkaitannya dan relatif masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
v. masalah rendahnya komitmen kelembagaan terkait, yang tidak hanya terkait dengan instansi pengelola (penanggung jawab) namun juga instansi lain yang terkait secara tidak langsung yang biasanya relatif kecil komitmennya walaupun peranannya cukup penting.
vi. masalah faktor pengaruh eksternal, seperti keterbatasan pengalokasian dana pendamping Pusat dan daerah, padatnya kegiatan struktural yang diemban pengelola proyek di masing-masing instansi, serta kebijaksanaan yang kurang sinkron/mendukung dan faktor rantai birokrasi (antara Pusat dengan daerah).
ii. Prinsip fungsionalisasi struktural kelembagaan, dengan memanfaatkan dan menguatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, untuk menjamin keberlanjutan penanganannya setelah selesainya proyek ini, yang pengalokasian kegiatannya diselaraskan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi terkait;
iii. Prinsip perencanaan aspiratif dan koordinatif, dimana mekanisme perencanaannya bersifat bottom-up planning yang didasarkan pada aspirasi daerah/masyarakat yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang terkoordinasi dan terpadu.
iv. Prinsip keberlanjutan, diharapkan perhatian dari pemerintah daerah terkait untuk dapat memperhitungkan kebutuhan dana pendamping yang diperlukan sebagai pendamping/penunjang kegiatan yang dibiayai melalui PHLN yang diperkirakan akan dapat ditarik. Pertimbangan ini sangat diperlukan mengingat bahwa penyediaan dana pendamping/penunjang tersebut, khususnya yang berasal dari dana asli daerah (PAD/APBD) akan sangat menentukan keberlanjutan dari kegiatan proyek pada saat proyek tersebut berakhir.
Terima kasih.